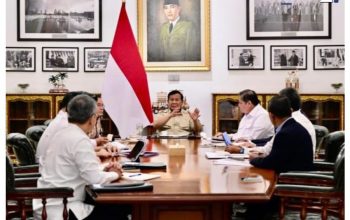“Marah, Bro?”
Aku hanya melirik Afif sekilas sebelum pura-pura sibuk dengan laptopku. Sejak kejadian tadi malam, aku tak bisa tenang bahkan tidur pun tak nyenyak. Kesal karena semua yang kulakukan tak membuahkan hasil sesuai harapan, sahabat yang seharusnya membantu justru semakin memojokkanku.
“Aku bukannya mau mengkhianati kamu sebagai teman, tapi aku tak tega melihat luka mendalam di mata seindah itu,” ucapnya sok puitis yang justru semakin memancing emosi dalam jiwa. Berani sekali dia menikmati keindah mata istri sehabatnya sendiri. “Sebaiknya kamu tobat dan balik deh sama istrimu sebelum aku beneran embat dia.”
“Bacot!” semburku yang sudah tak bisa menahan rasa kesal.
“Eh, aku nggak cuma ngebacot lho. Aku serius.” Afif menyengir lebar.
Afif adalah playboy, memuji wanita setinggi langit baik secara langsung maupun tidak sudah menjadi ciri dirinya. Dia bahkan bisa memuji ibunya Adam dengan kata-kata manis dan kami sama-sama tahu semua itu hanya omong kosong, tetapi kenapa hatiku terasa panas mendengar dia terus saja memuji El?
“Keluar dan jangan pernah muncul di hadapanku, sialan!” Bukannya pergi walau sudah aku usir, Afif justru menatapku sambil senyum-senyum, menggelikan.
“Sebenarnya kamu marah karena aku dan Adam nggak jujur sama El atau karena aku selalu memuji El?” Afif menaikkan ujung alisnya.
Pertanyaan sialan, sebab itu membuatku menanyakan hal yang sama pada diriku sendiri. “Kamu cemburu, ya?” tudingnya. Aku langsung mengambil name desk untuk dilemparkan padanya tapi pintu yang tiba-tiba terbuka menarik perhatian kami.
Sosok yang kami bicarakan muncul, masih dengan penampilan yang sama, pun dengan sorot matanya, berbinar terang.
“Eh, ada Kak Afif,” seru El seolah sangat senang melihat keberadaan sahabatku.
“Eh, El datang juga,” balas Afif diiringi senyum lebar, sampai ingin membuatku merobek mulutnya. “El bawa makan siang untuk Al ya?” Dia bertanya pada El tapi melirikku, seolah sengaja ingin memprovokasi.
“Iya, Kak.” El melangkah masuk dengan tenang, gamis panjang berwarna putih yang menutupi seluruh tubuhnya sedikit menyentuh lantai. Jika diingat-ingat, El lebih sering memakai pakaian warna putih atau hitam polos. “Kak Afif sudah makan siang?” tanyanya seraya meletakkan rantang di meja.
“Be_”
Aku langsung melotot tajam pada Afif hingga pria itu meralat, “Sudah, El.”
“Oh, baiklah. Mas Al pasti belum makan, kan? Makan dulu, Mas.”
Aku memicingkan mata pada wanita itu yang kini sibuk membuka rantang. Ini kali pertama El datang ke klinik dan dia datang sebagai istri yang sangat baik, seolah hubungan pernikahan kami sangat harmonis.
“El bawa buah juga, Kak Afif mau?” tawarnya yang kembali membuat Afif menyengir lebar.
“Kenapa kamu manggil dia Kak?” protesku, terucap begitu saja dari bibir.
“Kan Kak Afif lebih tua dari El, Mas,” kilahnya.
“Nggak usah sok dekat manggil pria lain Kak,” ketusku.
“Jadi harus manggil Mas gitu?”
Aku menggeram tertahan, apa dia tidak bisa memanggil nama saja?
“Aku suka panggilan apa saja dari El,” kata Afif yang entah sejak kapan sudah duduk di sofa, menikmati buah yang El bawa. “Kak, Mas, Abang, Say_”
Aku langsung menghampiri sahabat pengkhianat ini lalu menyeretnya keluar dari ruanganku. El sempat protes tapi aku tak peduli. “Pulang sana! Pacar-pacarmu nyariin tuh.”
Bukannya marah, Afif justru tertawa sambil menggigit potongan buah yang ada di tangannya. Aku langsung menutup pintu dengan kasar. Saat berbalik badan, aku melihat El yang kini duduk di kursiku, membuka laptop.
“Customer Mas Al cantik-cantik banget,” ujarnya.
“Namanya juga customer klinik kecantikan,” balasku.
“El juga mau ah perawatan di sini.”
“Kalau kamu mah mau perawatan di surga pun nggak akan jadi cantik,” cibirku.
“Oh ya? Awas ya nanti klepek-klepek kalau sudah melihat kecantikan wajah El.”
“HAHA HAHA!” Aku tertawa mengejek. El tak pernah memperlihatkan bahwa dia tersinggung atau terluka oleh kata-kata dan kelakuanku. Apa karena dia punya hati sekuat baja atau justru tak punya hati sama sekali?
“Pulang sana! Aku mau ketemu sama istriku yang sedang hamil,” ujarku, sengaja untuk membuatnya kesal. “Dia pasti sudah menunggu suami tercintanya pulang.”
“Oke.” Di luar dugaan, El setuju begitu saja. Wanita itu langsung angkat kaki dari ruanganku.
Tepat setelah El menutup pintu, Yara menghubungiku. Namun, aku sedang tak ingin berbicara dengannya. Aku mengabaikan panggilan tersebut dan mengecek jadwalku hari ini. Ternyata kosong.
Aku memang tak menangani banyak klien, hanya beberapa saja sehingga aku memiliki banyak waktu luang. Tentu saja hal itu kulakukan karena bekerja sebagai dokter kecantikan bukanlah karir yang kuinginkan, aku juga tak berniat mengais rupiah dari pekerjaan ini.
Apa pun yang kulakukan di sini hanya untuk memberikan alasan agar Papa marah karena dia ingin aku mengurus perusahaan, membangkang dari keringinannya adalah sesuatu yang harus kulakukan. Selain itu, aku memilih menjadi dokter kecantikan untuk mengenang mendiang ibuku karena dia juga seorang dokter kecantikan. Dia ingin punya klinik sendiri dan sudah mempersiapkan semuanya tapi maut tiba tanpa terduga, tak hanya merenggut nyawanya tapi juga merenggut kebahagiaanku.
Ponsel kembali berdering, masih Yara yang menghubungiku. Kali ini aku menjawabnya. “Ada apa, Yar?” tanyaku tak bersemangat.
“Sibuk, Mas?”
“Iya, ada apa?”
“Pengen salad ayam, Mas,” rengeknya.
Aku meringis. Apa wanita hamil memang manja seperti ini? Perhatianku langsung tertuju ke meja di mana ada rantang berisi makanan yang sudah Elma tata. Aku memeriksanya dan ternyata ada salad ayam di sana, ada buah apel yang sudah dipotong dan jeruk yang sudah dikupas, ada udang tempura. Bagaimana El bisa tahu kedua menu ini adalah favoritku?
“Aku ke sana sekarang,” ujarku lalu kembali menutup rantang.
Dari pada dibuang, lebih baik makan ini bersama Yara. Jika El tahu, dia pasti akan meradang. Sudah lelah memasak, eh kunikmati bersama selingkuhan.
Aku segera ke apartemen Yara, yang langsung disambut dengan pelukan hangat dan ciuman mesra olehnya. “Gila, kamu bawa masakan istrimu ke sini?”
“Kamu nggak mau makan masakan istriku?” Aku balas bertanya.
“Ya agak gimana gitu kalau kamu bawa makanan istrimu untuk istri keduamu ini.”
“Biarin aja, biar dia sakit hati.” Aku tersenyum puas. Yara memindahkan makanan ke piring. “Dia benar-benar membuatku kesal, entah apa lagi yang harus aku lakukan untuk membuatnya angkat kaki dari rumah dengan sendirinya.”
Aku mulai menikmati hidangan di hadapanku dan ternyata rasanya sangat enak. Sejak menikah, El selalu memasak di rumah, meja makan tak pernah kosong tapi tak pernah sekali pun aku mau memakannya. Aku selalu membeli.
Kulihat Yara juga makan dengan lahap.
“Aku heran sama El, dia itu punya hati atau nggak?” racauku seraya mengunyah, rasa kesal di dada masih bergejolak apalagi saat mengingat bagaimana dia memanggil Kak pada Afif dengan nada yang sangat … menggelikan. “Dia juga centil, sok akrab sama Afif. Manggil kakak lagi.”
Aku meneguk air setelah tanpa sadar menghabiskan semua makananku di piring. “Dia juga sudah berani datang ke klinik, mau apa coba? Mau sok jadi istri yang baik?” Aku tersenyum sinis. “Dia juga ngaku-ngaku hamil ke orang tuaku sambil tersenyum, benar-benar kurang ajar.”
“Kalau kamu kurang apa?” cetus Yara tiba-tiba yang membuatku mengernyit.
“Maksudnya?”
“Sejak tadi kamu hanya membicarakan El dan El lho, Al,” serunya
“Nggak lah!” elakku. “Aku cuma bilang ke kamu kalau istriku itu menjengkelkan, Sayang.”
“Cuma kamu bilang?” Yara terkekeh. “Sejak menginjakkan kaki di apartemenku, terus kita makan sampai selesai makan, kamu nggak berhenti membicarakan istrimu.”
Aku termangu. Rasanya tidak mungkin aku membicarakan El terus-terusan tapi ….
“Nggak sadar ya?” Yara geleng-geleng kepala sambil beranjak dari kursi, dia mengambil piring kotorku. “Lain kali aku rekam aja biar bisa kamu dengar sendiri seberapa panjang kamu berbicara tentang Elma. Dan asal kamu tahu, ini bukan kali pertama. Sebelum-sebelumnya juga begitu.”
“Nggak, aku … aku nggak bermaksud membicarakan dia,” kilahku. “Aku sangat membencinya.”
“Benci sama cinta beda tipis lho.” Kini Yara mencuci piring kotor kami. “Kamu tahu kenapa? Karena orang yang kamu cintai dan kamu benci sama-sama akan selalu ada di pikiranmu.”
“Itu nggak benar.” Aku langsung menghampiri Yara, memeluknya dari belakang. “Aku nggak mungkin mencintai keponakan pelakor itu, dia pasti sama saja seperti tantenya. Mau menikah denganku demi harta.” Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan kamera lalu memotret diriku yang kini mengecup pipi Yara dengan mesra.
“Buat apa difoto?” kekeh Yara. “Kamu bisa mengecupku kapan pun kamu mau.”
Aku hanya tersenyum samar lalu kembali duduk di kursi, tanpa ragu, kukirim foto itu ke nomor El, tak lupa rantang yang sudah kosong juga kufoto.
[Istriku suka masakanmu, kami makan bersama dan menghabiskannya.]
Aku tersenyum sinis, sudah kubayangkan wajahnya pasti memerah karena amarah dan air mata mungkin mengalir di pipinya.
Ting
Ting
Dua pesan masuk, segera kubuka dengan tak sabar
[Mesranya …. ]
[Tapi apa nggak takut aku racuni makanannya?]
Aku langsung terbelalak. El tidak pernah menawarkan makanan padaku walaupun sudah memasak di rumah, tapi hari ini tiba-tiba dia membawakan makanan ke tempat kerjaku.
Apa dia sungguh … meracuniku?
Pandanganku tiba-tiba buram, kepalaku pusing dan perutku bergejolak. Mungkinkah racunnya sudah bereaksi?
Oh Tuhan, apakah ini hukuman atas perbutanku pada El sejak tiga bulan lalu?